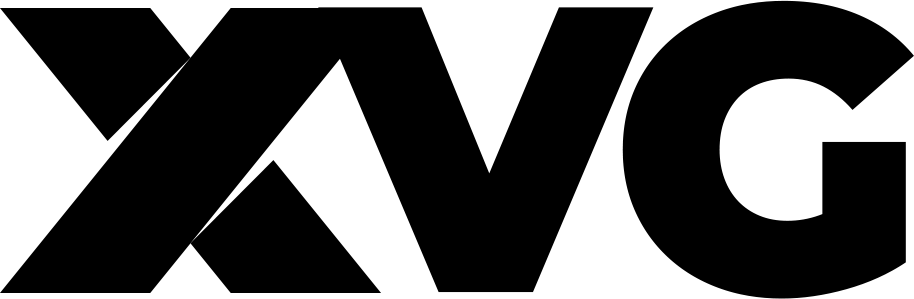Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, bantaran Sungai Ciliwung di Banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyimpan cerita tersendiri. Meski tidak pernah benar-benar sunyi, area ini menawarkan pemandangan yang kontras dengan gemerlapnya kota. Di sini, hamparan kebun kecil seolah menjadi potongan pedesaan yang tersesat di tengah metropolitan. Gubuk-gubuk kecil dan rumput liar menandai batas tanah yang belum terolah, sementara deru kendaraan di kejauhan menjadi latar belakang yang tak pernah berhenti.
Di antara kontras tersebut, berdirilah Jahri, seorang pria berusia 63 tahun yang akrab disapa Pak Jangkung oleh warga sekitar. Dengan tubuh tinggi dan kurus, Jahri memegang cangkulnya seolah itu adalah bagian dari tubuhnya yang tak terpisahkan. Selama lebih dari dua dekade, ia menggantungkan hidupnya pada lahan di bantaran Ciliwung, meski tanah tersebut adalah milik negara. Di sinilah ia menanam nafkah, harapan, dan alasan untuk terus bertahan di Jakarta.
Bertani di bantaran sungai bukanlah hal baru bagi warga sekitar. Namun, kondisi lahan yang dulu kumuh membuat banyak orang enggan mengolahnya. Jahri mengenang masa ketika pemerintah meluncurkan program pemberdayaan lingkungan sekitar awal 2000-an. Lahan kosong di pinggir kali dikelompokkan dan diawasi oleh ketua kelompok, lalu dibagikan untuk digarap warga. Program ini menyediakan pupuk, bibit, dan modal usaha bagi masyarakat yang ingin bertani di tanah pemerintah.
Lahan yang dikelola Jahri mencapai hampir satu hektar, terbagi dalam beberapa petakan. Tanaman yang ia garap tidak jauh berbeda dari petani pinggiran kota lainnya, seperti kangkung, bayam, kemangi, kenikir, dan beberapa pohon pisang. Namun, tantangan terbesar bukanlah tenaga atau modal, melainkan risiko banjir. Ketika banjir besar datang, air menyapu seluruh petakan lahan, mengubah tanah menjadi lumpur pekat. Proses pemulihan membutuhkan waktu panjang dan biaya tidak sedikit.
Hasil panen Jahri dijual langsung ke berbagai pasar tradisional seperti Pasar Jati, Pasar Gili, Pintu Air, dan Impres. Setiap kali menjual, ia membawa ratusan ikat sayuran dengan harga Rp 2.000 per ikat. Dalam sekali panen, Jahri bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp 7-8 juta jika semua petak lahan ditanami. Namun, dari hasil itu, ia masih harus membaginya untuk kebutuhan modal dan operasional.
Bantaran sungai tidak pernah steril dari gangguan. Ada preman dan tangan-tangan iseng yang menebang pohon diam-diam saat malam. Jahri pernah didatangi beberapa preman, namun ia memilih melawan dengan cara yang ia sebut sebagai “kebenaran”. Kerentanan ini bukan sesuatu yang ia takuti, melainkan ia anggap sebagai bagian dari risiko hidup di lahan yang tidak bisa ia klaim sebagai milik pribadi.
Kawasan bantaran kali tempat Jahri menggarap lahan beberapa kali masuk agenda pembersihan. Ia menyebut bahwa pernah ada rencana pengerukan kali. Jika itu terjadi, kebun yang ia rawat selama puluhan tahun bisa hilang dalam sehari. Namun, ia tidak mengeluh. Baginya, itu risiko paling wajar bagi orang yang menggarap tanah milik negara. Ia hanya berharap jika ada pembenahan, pemerintah bisa tetap mempertimbangkan ruang bagi warga untuk tetap berkebun.
Menurut pengamat tata kota, Yayat Supriatna, urban farming memiliki fleksibilitas yang tinggi. Lahan yang tersisa di perkotaan bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman hias, pangan, atau buah-buahan. Urban farming tidak sekadar soal menanam tanaman, tetapi juga bisa menjadi sarana membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kota.
Kebun urban farming yang dikelola Jahri kini menjadi oase hijau di tengah kepadatan pemukiman. Selain menambah estetika kawasan, kebun ini juga menjadi sumber tambahan bahan pangan bagi tetangga sekitar. Kehadiran kebun ini menciptakan interaksi sosial yang lebih hangat antarwarga, karena hasil panen dibagikan dan dimanfaatkan bersama. Warga berharap kebun ini dapat terus lestari dan tidak digusur, sehingga manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang.
Dengan segala tantangan dan harapan yang ada, kehidupan di bantaran Sungai Ciliwung menjadi potret ketahanan dan semangat untuk terus bertahan di tengah kerasnya kehidupan kota. Kebun kecil ini bukan hanya sekadar lahan pertanian, tetapi juga simbol harapan dan keberlanjutan bagi warga yang menggantungkan hidup padanya.